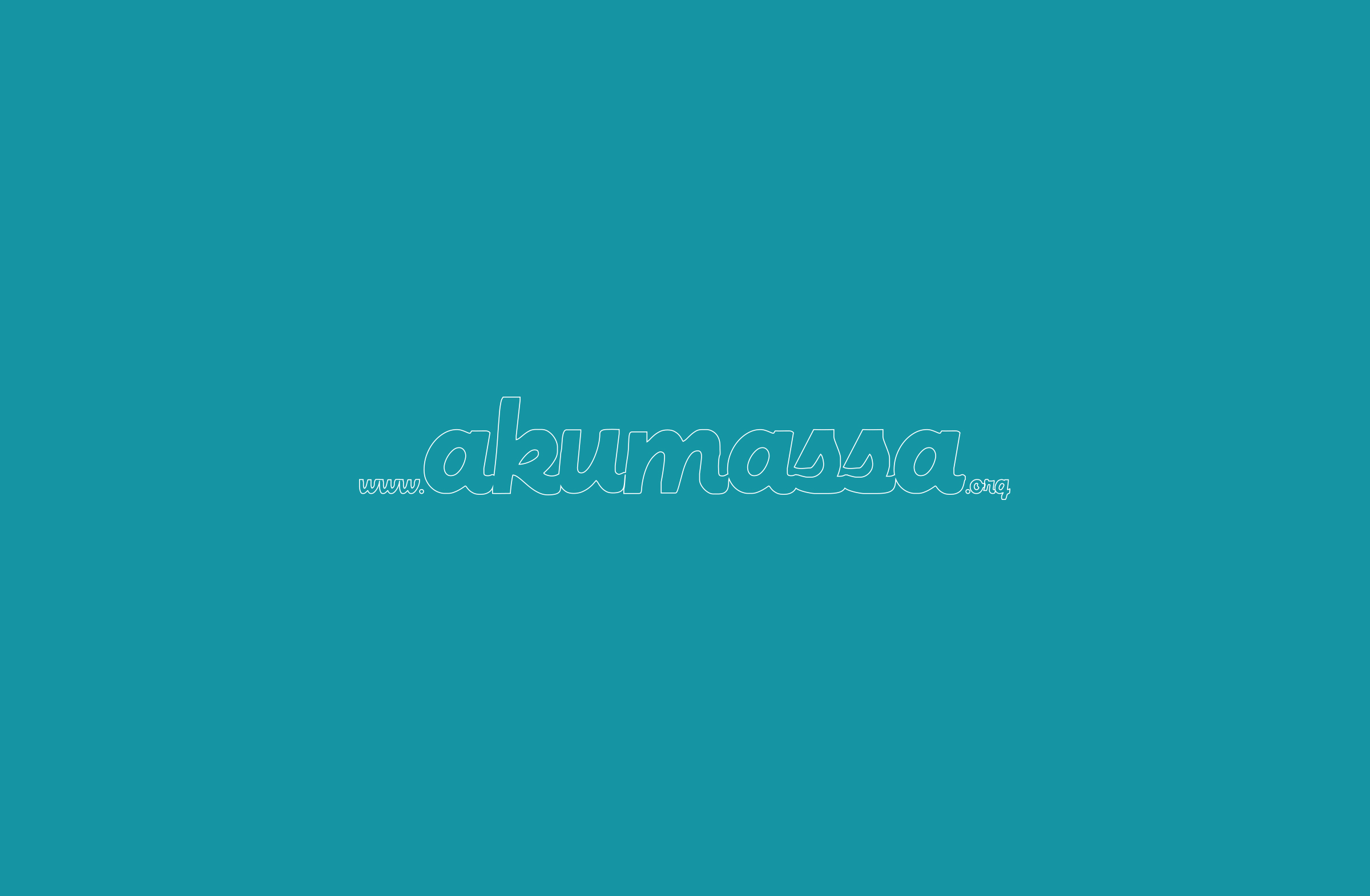Kereta dan massa. Mungkin terbayang dalam benak kita tentang rangkaian gerbong dengan penumpang yang berjejalan di dalamnya. Atau puluhan orang menunggu datangya kereta di stasiun. Itu semua benar. Tapi yang akan aku ceritakan saat ini adalah tentang kereta dan massa yang lain. Yaitu, tentang para pemulung atau pengumpul barang bekas yang bermukim di pinggir rel kereta sepanjang Lenteng Agung. Mereka, walau tidak berhubungan langsung atau menjadi penumpang kereta, tapi sangat dekat dan terbiasa dengan lalu-lalang barisan gerbong kereta yang lewat di pinggir rumahnya. Terkadang, mereka juga menjadi pemandangan tersendiri bagi kita saat berada di dalam kereta, sebagai ornamen tambahan dari sebuah lukisan ‘kota dengan gedung-gedung pencakar langit’.

Rel kereta yang berada di wilayah Lenteng Agung
Perkenalanku dengan mereka bermula karena keperluan pembuatan video akumassa. Mereka terdiri dari beberapa keluarga yang dikepalai oleh bos kecil pengumpul sampah, bernama Pak Yumadi. Pak Yumadi lebih dikenal dengan sapaan Pak Komplong. Menurutnya, ‘komplong’ berarti kaleng kosong. Karena dahulu sebelum ia menjadi bos pemulung, ia juga bekerja mencari barang bekas, salah satunya kaleng kosong.
Pak Komplong berkulit hitam dan bertubuh sintal. Ia berasal dari Ngawi, Jawa Tengah. Di rumah sepetak yang terletak di pinggir rel kereta itu ia tinggal bersama istrinya. Sedangkan kelima anaknya tinggal bersama neneknya di kampung. Pak Komplong bercerita kepadaku tentang asal mula ia tinggal dan menjadi bos pemulung di pemukiman semi permanen di pinggir rel kereta api Lenteng Agung.
“Dulu tahun 70-an saya kerja jadi Supir bus Kopaja 600, kalau sekarang namanya Kopaja 616. Karena upahnya tidak sebanding dari capeknya, saya berhenti jadi supir, lalu coba memulung. Awalnya saya ikut bos di Sawah Besar. Tapi setelah saya kenal sama Pak Slamet, saya mengontrak bangunan ini dan mengepalai pemulung-pemulung di sini. Pak Slamet itu pensiunan Polisi. Dulu bangunan punya dia ini dijadikan tempat bermain Billiard. Tapi setelah adanya pembangunan jalan raya Lenteng Agung menuju Pasar Minggu ini, sekitar tahun 80-an, tempat Billiardnya ditutup. Karena jalannya lebih tinggi dari bangunan.”
“Dari tahun berapa Bapak di sini?” tanyaku.
“Udah 6 tahun yang lalu. Tadinya cuma bangunan satu ini aja yang bekas tempat Billiard, terus saya bangun rumah-rumah petak lainnya buat para pemulung yang lain,” jelas Pak Komplong.

Rumah-rumah petak semi permanen
Dari ceritanya juga aku mengetahui bahwa ia mengontrak bekas bangunan tersebut seharga 7,2 juta Rupiah per tahunnya. Kenapa aku bilang ‘bekas’? Karena memang bangunan yang ditempati Pak Komplong sudah tidak karuan bentuknya. Yang terlihat sebagai sisa bangunan tempat Billiard hanyalah dinding-dinding penuh coretan. Sementara atapnya adalah tambal-tambalan hasil kreativitas Pak Komplong untuk menahan bocor saat hujan tiba.
Seperti dugaanku, bangunan bekas tempat Billiard itu memiliki ijin yang syah. Namun lain halnya dengan bangunan semi permanen di sekitarnya. Bangunan yang menjadi rumah-rumah para pemulung itu berdiri tanpa ijin dan harus siap digusur suatu saat nanti.
Menurut Pak Komplong, mereka yang tinggal di rumah-rumah semi permanen itu berjumlah 14 orang. Walaupun saat aku berada di sana aku hanya menjumpai beberapa di antaranya. Yaitu, Mbak Iis, Mas Andri, Bu Aas, Arif, Yulis, Mas Yono, Mas Ujang, Pak Komplong beserta istrinya, serta beberapa orang lagi yang aku tak tahu namanya.
Di antara para pemulung di sana, yang paling menarik perhatianku adalah Keluarga Mas Andri. Ia merupakan suami dari Mbak Iis yang tinggal di rumah semi permanen paling ujung dari blok bangunan rumah-rumah tersebut. Karena hampir setiap hari aku melewati gang kecil di sebelah rumah Mas Andri untuk menyeberangi jalan kereta api dan menuju ke ruas jalan seberangnya, yaitu ruas jalan raya Lenteng Agung menuju Depok. Saat aku melewati gang itu, aku sering kali mencium bau masakan dari tungku di dapur rumah Mbak Iis yang belakangan aku ketahui ternyata merupakan dapur bersama.

Dapur bersama yang terletak di samping rumah Mas Andri
Mas Andri dan Mbak Iis tinggal bersama seorang anaknya bernama Yulis. Tapi sudah seminggu ini mereka sedang dikunjungi oleh Ibu Aas, ibu kandung Mbak Iis dan adik bungsunya, Arif. Sebelum menjadi pemulung, Mas Andri sempat memiliki usaha service handphone di sebuah mall. Namun usahanya bangkrut karena tak mampu bersaing dengan usaha sejenisnya. Di tengah kebingungannya ia bertemu Pak Komplong dan bekerja dengannya hingga kini. Mas Andri adalah tamatan SMA. Di usianya yang kini 26 tahun, Mas Andri masih ingin meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. “Pengennya sih kuliah, Mbak…” ujarnya beberapa kali ketika mengobrol denganku.

Dari kiri ke kanan: Mbak Iis, Yulis, Mas Andri, Arif, Ibu Aas

Gerobak milik Mas Andri
Setiap hari sekitar pukul 11.00 WIB Mas Andri pergi dengan gerobaknya untuk mencari barang-barang bekas yang bisa dijual. Misalnya gelas dan botol plastik air mineral, kardus, setrika bekas, besi-besi atau tembaga, hingga Televisi rusak pun ia angkut ke gerobaknya. Mas Andri biasa berjalan kaki mencari barang bekas di sekitar Lenteng Agung, Tanjung Barat, dan Pasar Minggu. Ia pulang ke rumah sekitar pukul 04.00 WIB esok paginya, kecuali pada hari-hari menimbang dan menjual hasil tangkapan, alias barang bekas, kepada Pak Komplong. Biasanya pada hari tersebut ia libur di rumah dan ikut membantu istrinya membersihkan dan mengelompokkan jenis barang bekas untuk dijual ke Pak Komplong.
Barang bekas yang telah ditimbang per kilonya oleh Pak Komplong kemudian dipilah-pilah lagi olehnya. Misalnya dari bagian setrika rusak, Pak Komplong memisahkan baut, tembaga, dan plastik ,yang merupakan partikel-partikel setrika tersebut, sesuai dengan jenis bahan bakunya. Barang-barang berbahan baku Tembaga merupakan yang paling mahal dijual per kilonya, yaitu sekitar Rp. 14.600,-.

Barang bekas yang sudah dikelompokkan ke dalam karung
Seperti kataku di awal tadi, Pak Komplong merupakan bos kecil. Karena itu barang-barang yang sudah terkumpul olehnya biasanya akan diangkut oleh truk pick-up suruhan bos besar yang memang sudah menjadi rekan bisnis Pak Komplong. Menurut Pak Komplong, barang-barang bekas itu diangkut ke daerah Bekasi dan Tangerang. Ia hanya tahu nasib barang-barang bekas itu sampai diangkut ke truk. Selanjutnya ia tidak tahu dan tidak mau tahu.
Kembali ke keluarga Mas Andri dan Mbak Iis. Pasangan suami istri yang begitu ramah ini punya kisah cinta yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Mbak Iis lebih dahulu menjadi pengumpul barang bekas setelah ia putus sekolah sampai kelas 4 SD di Bogor, kota kelahirannya. Mbak Iis kemudian merantau ke Jakarta bersama saudaranya, dan menjadi pemulung. Mungkin karena saat itu belum ada program sekolah gratis atau kesadaran masyarakat akan pendidikan masih terlalu rendah.

Mas Andri dan Mbak Iis di tengah kegiatannya
Mbak Iis sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan memulung di beberapa daerah di Jakarta. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Mas Andri yang juga sedang memulung. Keduanya menikah di Pondok Labu, rumah kedua orangtua Mas Andri, pada tahun 2003. Kemudian ikut tinggal di rumah semi permanen saat ini, yang tadinya ditempati oleh Mas Andri seorang.
Mereka menjadikan sepetak rumah itu tempat yang serbaguna. Ketika siang, kasur-kasur dilipat dan ruangan dijadikan tempat ngobrol santai. Jika jam makan tiba, ruang tersebut berubah menjadi ruang makan bersama, dan kasur kembali digelar pada malam harinya. Di dalam ruangan itu, ada tiga buah kipas angin, karena ruangan itu beratap pendek jadi terasa panas ketika siang.

Arif saat ingin tidur siang

Suasana di dalam rumah Mas Andri
Selain itu, ada dua buah meja. Satu meja tempat memajang boneka milik Yulis, foto dan beberapa hiasan lainnya. Ada yang menarik dari benda-benda kecil di atas meja itu. Yaitu sebuah handphone hasil rakitan Mas Andri. Telepon itu tidak menggunakan baterai dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Fungsinya seperti telepon rumah. Mas Andri memperbaiki handphone tua tersebut dengan caranya sendiri. Mungkin sisa-sisa ilmu menjadi tukang service handphone, sebelum ia menjadi pemulung.

handphone unik hasil kreasi Mas Andri
Satu meja lainnya digunakan sebagai tempat menyimpan makanan sekaligus menjadi rak piring. Ada pula sebuah lemari mini tempat menyimpan baju keluarga itu. Saat berada di dalam ruangan tersebut, aku membayangkan seperti apa rasanya saat kereta melewati rel di samping rumah mereka. Dan saat kereta itu benar-benar lewat, ternyata rasanya biasa saja. Getaran-getaran kereta memang terasa seperti gempa kecil dengan irama teratur, namun tidak menakutkan.