“Perkenalkan, nama saya Salim. Situ namanya siapa? Dan apa kabarnya?”
Sebelah barat Randublatung, tepatnya Desa Sumber Balong, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Aku disana malam itu.
Malam itu aku memasuki sebuah desa yang gelap. Kuperkirakan ada 20 rumah di sana, saling berhadapan. Umumnya, satu muka rumah ada tumpukan jerami, mungkin untuk makanan sapi peliharaan mereka. Desa itu tidak terlalu jauh dari jalan utama. Kami menyusuri jalan setapak dengan sepeda motor tua buatan Jepang berwarna merah. Di ujung jalan setapak itu ada sebuah bangunan bercat putih yang pintunya terbuka. Ada cahaya berasal dari lampu neon menerangi bagian depan rumah, tampak sekitar 5 orang bapak-bapak sedang mengerjakan sesuatu dengan batangan bambu dan kayu. Kami parkir di depan sebuah rumah papan yang tertutup. Di sisinya ada sebuah rumah joglo yang pintunya dibiarkan terbuka. Kami pun turun dan menghampiri mereka. Kawanku bertanya dalam Bahasa Jawa yang aku dapat mengira-ngira maksudnya, ”Permisi, Kang Salim ada atau tidak?”
“Oh, ada,” jawab salah seorang lelaki yang yang berperawakan sedikit tambun dan berkulit hitam legam. Dia bertelanjang dada dan mengenakan celana ukuran tiga perempat berwarna hitam. Kulihat salah seorang bapak masuk ke dalam rumah joglo tadi , lalu keluar dengan diikuti oleh seorang pria yang tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 155 cm. Dia langsung mengetuk pintu rumah tempat kami memarkir motor.
Seorang wanita membukakan pintu. Dia mengenakan daster seperti yang biasa digunakan ibuku di rumah. Senyum seiring terbukanya pintu, tersungging dari wajah yang bersahaja. Kami pun dipersilakan masuk dan duduk di kursi panjang berwarna coklat dengan meja yang ukurannya sama dengan kursi itu. Tak sampai lima menit, muncul sesosok pria berperawakan kurus tinggi, mengenakan sarung dan kaus oblong berwarna gelap, langsung menyalami kawanku.
“Bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak jumpa,” ucapnya.
Lalu dia berpaling ke arahku sambil bertanya dalam Bahasa Jawa yang menurutku sangat halus sekali dan tidak kumengerti. Tapi aku menduga dia menanyakan namaku, dengan senyum sangat ramah dan menjabat tanganku dengan hangat sekali. Aku sedikit bingung, lalu menoleh kearah kawanku sambil berusaha menjawab pertanyaannya dengan mimik bingung,
“Saya Gelar, Pak. Lalu dia memperkenalkan namanya, “ Saya Salim.”
Pak Salim duduk di kursi barisan kanan paling ujung, berhadapan denganku. Perkenalan dilanjutkan dengan Si Ibu yang tadi datang menyalami dan menanyakan namaku dengan nada yang sangat merdu masuk ke telingaku. Setelah aku menyebut namaku dia pun menyebutkan namanya. Namun sialnya, saat aku menuliskan ini, aku lupa siapa namanya. Maaf, mengingat nama seseorang adalah kelemahanku.
Si Ibu duduk di kursi kayu panjang berwarna coklat yang mirip kursi yang sering ku temui di warung-warung nasi, menghadap ke sisi lebar meja. Pak Salim masuk ke dalam, lalu kembali dengan membawa kendi dan sebuah kain lap untuk membersihkan meja yang ada di depan kami.
Tak lama kemudian muncul seorang anak perempuan manis, berusia sekitar spuluh tahun, menghampiriku. Dengan suaranya yang tipis dia bertanya persis seperti yang dilakukan orang tuanya padaku sebelumnya. Aku pun menyebutkan namaku kembali dan dia memperkenalkan dirinya tak lupa senyum bersahabat selalu terlihat dari tiap individu yang ada di rumah ini. lalu anak itu duduk di samping ibunya. Kami pun melanjutkan percakapan. Temanku memperkenalkan kembali siapa aku dalam bahasa Jawa, dan mereka pun tersenyum karena aku tidak mengerti Bahasa Jawa, aku pun ikut tersenyum. Pak Salim bertanya sesuatu padaku, aku langsung memalingkan wajahku pada temanku sedikit memberi isyarat ketidak mengertian. Temanku menerjemahkan, “Dari mana asalmu, katanya?” Oooh, aku langsung menjawab, “ Jakarta, Pak, dan kampungku di Cianjur.” Pak Salim menyambung, ”Ooo..wong sundo, tho?” Ruangan pun dipenuhi dengan renyah tawa kami.
Kemudian aku bertanya, “Sering ya, Pak, orang datang ke sini?” Pak Salim menjawab dalam Bahasa Jawa yang langsung diterjemahkan oleh temanku, “Sering. Kemarin ada orang Kompas (surat kabar harian-red) ke sini untuk meliput pembuatan pupuk alami.” Lalu aku kembali bertanya, “Biasanya untuk bertani apa saja yang orang sini lakukan?” Pak Salim pun menjawabnya dengan senyuman, lalu berkata, “Untuk tani…” lalu dia mengambil sebuah dirigen yang diisi dengan cairan pestisida. “Terbuat dari apa?” Tanyaku. “Oh, ini terbuat dari tembakau yang sudah diekstrak dan ditambah sedikit sabun colek”. Hmm…pantas aku melihat di sudut rumah sebelah kiri di penuhi dengan tumpukan tembakau, memenuhi hampir seperempat ruang tamu.
Di samping tumpukan tembakau terdapat dua sepeda ontel dan di sebelahnya ada dua sekat ruangan dari papan dengan pintu yang ditutup dengan kain warna merah hati yang berfungsi sebagai pembatas mata, agar ruangan yang menurut perkiraanku adalah sebuah kamar itu tidak terlihat dari ruang tamu. Di dinding depan ruangan tadi dipajang foto sekumpulan orang memakai baju atasan sejenis jas berwarna hitam. Di bagian dalamnya mereka mengenakan kemeja putih. Mereka berpose dengan formasi satu baris di belakang berdiri dan satu baris di depan berjongkok, mirip foto kenanganku saat wisuda dulu.
Pak Salim menceritakan desanya yang panen buah timun suri. Aku menyela dengan pertanyaan tentang pestisida tadi, “Tapi pestisida in ampuh, Pak? Hama apa saja yang dibasmi?” Pak Salim menjawab dengan senyumnya yang khas, “Oo, ampuh tenan. Belalang, walang sangit, biasanya kalah!” Bu Salim ikut menambahkan omongan Pak Salim dengan sangat halus, lalu bergegas pergi ke belakang sambil bercerita lagi bahwa Bapak pernah ditawari kerja di kota, di bidang pertanian. Si Bapak langsung menolak, “Lha wong di sini saya juga kerja kok, Pak,” ungkapnya bercerita. Kami pun tertawa.
Tak lama kemudian Si Ibu kembali dengan membawa nampan berwarna merah, berselisihan dengan anaknya yang masuk ke kamar, “Ini, silakan diminum”. Di atas nampan terdapat empat gelas kopi dan satu gelas teh., kedua-duanya tubruk. Aku dan temanku di beri kopi dan kami langsung meminumnya, srlruuup…ahh. Aku mengambil rokok dari tas jinjingku. Hisapan pertama nikmat sekali, pas dengan aroma kopi yang khas. Aku bertanya, “Kopi Jawa, ya?” Bapak yang duduk di depanku mengiyakan disambut oleh tawa Pak Salim yang duduk di sebelahnya. Ada sekelumit pertanyaan dalam hatiku, penasaran dengan keberadaan gelas ke lima.
Aku menoleh ke arah pintu keluar, muncul sosok pria berbaju hitam seperti baju silat dan celana pangsi juga berwarna hitam, sebagaimana sosok Orang Samin yang pernah aku lihat di internet. Bawah hidungnya ditumbuhi kumis dan giginya menguning layaknya seorang perokok. Dia juga melakukan ritual perkenalan yang sama terhadapku, tentunya dengan senyum hangat khas orang timur mengiringi. Ia duduk di pojok berhadapan dengan Pak Salim. Aku berpikir, oo..mungkin kopi ini buat dia. Sedikit penasaran tentang segelas kopi sudah terjawab. Ia bercerita tentang Mbah Tarno, seorang sesepuh yang salin (meninggal dunia, menurut istilah daerah itu), setelah mengunjungi delapan orang yang ditahan akibat penolakan pembukaan sebuah pabrik semen di Pati, jawa Tengah oleh kaum petani. Obrolan itu mengalir dalam bahasa Jawa yanga sama sekali tidak kumengerti. Sesekali mereka terdiam disayupi suara tokek dan jangkrik yang senantiasa memecah syahdunya malam. Lalu aku bertanya, “itu yang di luar bikin apa, Pak”. “Oo, itu sedang membuat sesek, jembatan kecil yang dianyam dari kayu untuk di sawah.”
Aku terdiam lagi memperhatikan ruangan yang sedang aku tandangi. Di belakang Pak Salim ada sebuah tv yang tidak dihidupkan, menghadap ke arah kami. Aku pun tertuju pada sebuah poster yang bertulisakan aksara Jawa dan angka, terpajang di tembok kayu persis di sebelah depan kanan tempat ku duduk. Lalu aku melihat jam yang ada di sebelah poster itu menunjukkan pukul 21.30 WIB. Aku resah dengan getar telepon genggam yang ada di tas jinjingku. Aku tak berani mengangkatnya karena aku tidak tahu kebiasaan keluarga disini yang menurutku sangat tradisional. Aku memakan suguhan yang dihidangkan dengan sangat ramah dan raut wajah tukus, yaitu kue yang terbuat dari kelapa dengan rasa yang mirip wajik namun agak keras. Ada lagi yang berbentuk pipih, disainnya sedemikian rupa dan biasa disebut ‘kembang goyang’. Manis. Dan aku kembali meneguk kopi yang tinggal setengah, menyalakan sebatang rokok mentol yang saat ini sahamnya telah dikuasai Philip Morris.
Foto Itu, Aku Pernah Melihatnya Sebelum Hari Ini
Seketika juga pandangan kuarahkan ke bagian tengah rumah Pak Salim. Ada tiga foto terpajang di sana. Di sebelah kiri, foto Bu Salim. Sebelah kanan foto Pak Salim. Di antaranya terpajang foto yang tidak asing dan melekat di kepalaku. Aku berusaha menerka siapa itu. Dan, bingo! Ya! Itu adalah Samin Surosentiko, yang tak asing lagi karena aku pernah membacanya di buku dan internet. Beliau adalah tokoh masyarakat yang menolak pajak yang dikenakan oleh pemerintah kolonial jaman Belanda, sekitar tahun 1859-1914-an, sekarang dikenal dengan nama Samin.

Samin Surosentiko
Samin adalah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Indonesia. Sebagai gerakan yang cukup besar Saminisme tumbuh sebagai perjuangan melawan kesewenangan Belanda yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk perluasan hutan jati. Saat ini keberadaan masyarakat ini sudah mulai tersingkir dari perkembangan massa bahkan di daerahnya sendiri.
Ya, sekarang aku sedang berada di Desa Samin, yang biasa disebut oleh masyarakat luar Samin Sedulur Sikep. Tidak menyangka, berada di tengah mereka saat ini, aku merasakan hangatnya kembali sebuah tradisi yang tidak kutemukan di Jakarta. Yah sebuah romantisme yang membuatku seolah damai sementara jauh dari hingar bingar rutinitasku di sana. Nyaman dan syahdu.
Tak lama, aku pun pamit. Semua mengantar kami sampai ke pintu dan kembali jabat tangan hangat dan diiringi kata dalam Bahasa Jawa seperti, “Terima kasih sudah berkunjung…”
Sangat berkesan walaupun sesaat namun sangat abadi dan membekas. Sepertinya aku akan merindukan tempat itu, yah, kembali ke alam sadarku.
Sepanjang perjalanan aku bertanya pada kawanku tentang maksud dari kopi itu, diperuntukkan untuk siapa. Lalu dia menjelaskan dengan fasih, “ Kopi empat dan teh satu itu diberikan untuk cadangan, dalam artian, kalau kamu tidak suka kopi maka teh itulah buat kamu”. Hmm…ternyata Orang Samin sangat penuh perhitungan dan santun dalam hal yang dianggap sepele oleh masyarakat di luar desa dan jelas di kotaku. Perhitungan demikian sudah tidak ada. Sebagian besar mereka hanya tulus di wajah dan membunuh dibelakang kepala.
Mungkin karena Orang Samin selalu menerapkan sebuah negara bathin yang jauh dari sikap drengki srei, tukar padu, dahpen kemeren. Sebaliknya, mereka hendak mewujudkan perintah ‘lakonana sabar trokal. Sabari dieling-eling. Trokali dilakoni’.
Yang dalam arti Bahasa Indonesia versiku ‘sebuah negara bathin harus jauh dari sikap iri, dengki, saling melengkapi dan tidak suka mencuri, konsep perintah, dijalani dengan sabar yang sabar dan menjalani setiap cobaan’.
Sebuah konsep humanis yang terlupa oleh orang di luar sana, khususnya kota besar yang mungkin mempunyai pandangan untuk hidup harus dekat dengan pemimpin dan pandai mengambil hati. Sedangkan dalam meraih kuasa dengan menghalalkan segala cara (Rhoma Irama sekali..) termasuk aku yang masih perlu belajar tentang hidup.
Ya, Samin tetap Samin. Dan kita tetap kita. Setiap ‘aku’ dalam ‘massa’ mempunyai sejarah yang bisa ditulis sendiri, dan Samin sudah masuk setidaknya dalam hitungan jam dan tercatat dalam sejarahku saat ini.



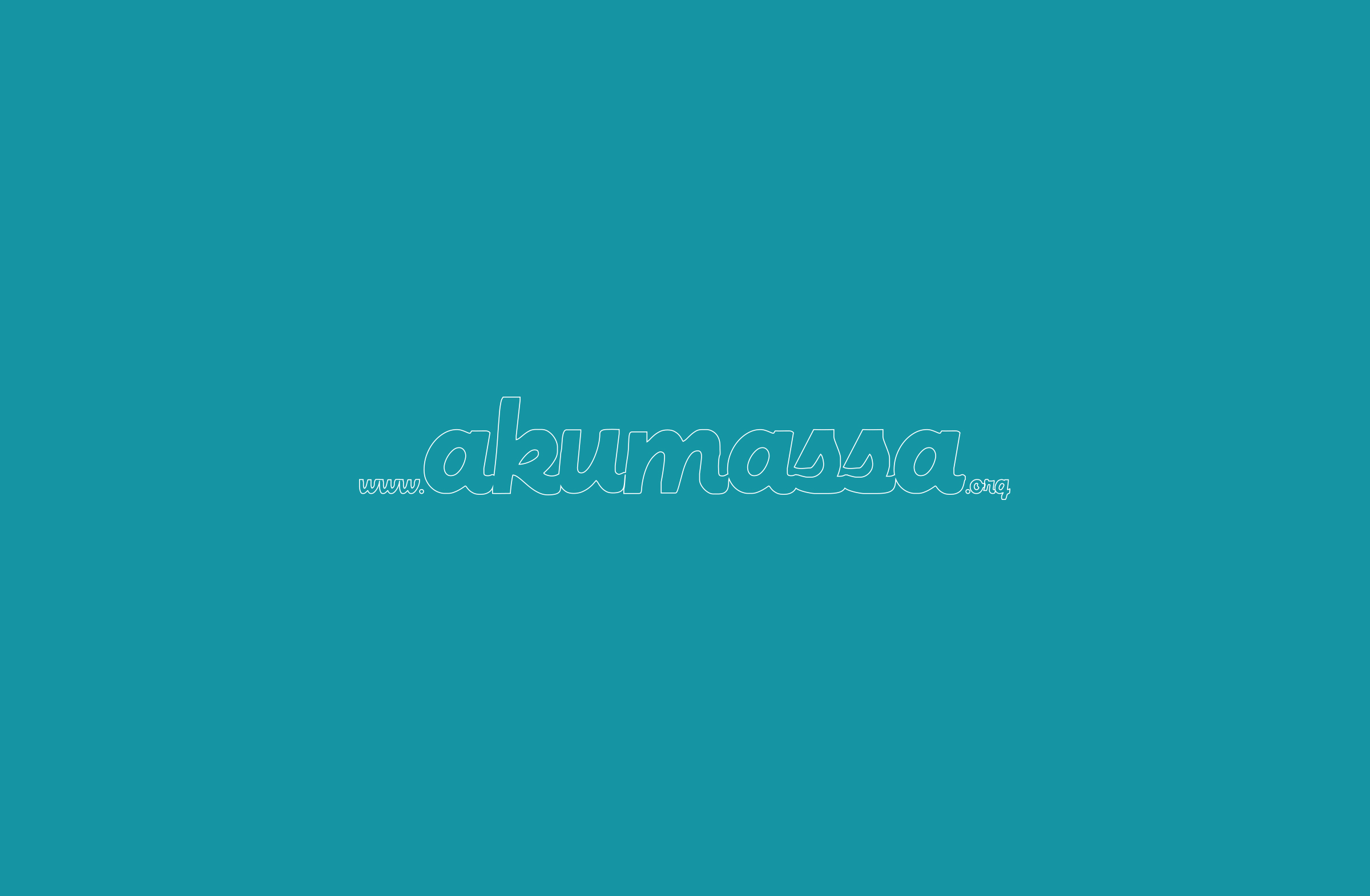
gaswat….. membaca ini serasa di tengah kaum samin yang jauh dari sikap drengki srei, tukar padu, dahpen kemeren.!!!
sing penting lakonana sabar trokal. Sabari dieling-eling. Trokali dilakoni!
wah seru juga tu lar..kaum samin dan “negara batin” nya..
kang kongkon yo kang nglakoni(kamumenyuruh ya kamu harus melakukan lebih dulu)sedulur sikep(samin)
Kaum Samin telah membangkang berbareng dengan Perang Aceh paling awal. pada awal abad 19, berarti kurang lebih ia telah membangkang selama seperempat abad sejak perang Aceh pecah. Bila dilihat dari awal bergeraknya, boleh jadi kaum Samin adalah orang-orang yang setia pada Diponegoro; Karena setelah Perang Diponegoro(1825-1830) padam, pada abad itu juga Samin lahir hampir berbarengan perang Aceh.
Awal abad 19 suasana di Hindia genting. Bali melakukan perlawanan terhadap Belanda, perang itu yang kita kenal dengaan Puputan Klungkung. Sedang para petani pemberontak, yang menamai dirinya golongan Samin, di Jawa tengah, berpusat di desa Klopoduwur di selatan kota Blora, pun dihadapi Belanda dengan senjata.
Petani sederhana dengan kekuatan limapuluh ribu jiwa itu, setelah seperempat abad melawan, saat itu kalah. mereka buang senjata tajam dan tumpul mengambil senjata baru yang lebih tumpul; Pembangkangan sosial terhadap semua ketentuan dan perintah Gubermen.
Mereka menolak membayar pajak, menolak rodi dengan semua aliasnya, dan dengan sukarela berbondong-bondong masuk dan keluar dari penjara. Mereka tebangi hutan dan mendirikan bangunan tanpa mau minta ijin. Gubermen kualahan.
Akhirnya Gubermen mengambil kebijaksanaan; membiarkan mereka dengan gaya hidupnya yang baru, selama mereka tidak angkat senjata mengganggu keamanan dan ketertiban Gubermen, Pemerintah, dan perabotnya.
sumber; Jejak Langkah, Pram.